
Alquran sebagai kitab suci dipandang sebagai teks kanon oleh umat Islam. Ia menjadi petunjuk dan referensi utama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Permasalahan mulai timbul ketika “cara membaca” Alquran ditempuh dengan pelbagai macam metode dan teknik. Cara pembacaan dengan pendekatan, metode, teknik, ataupun angle yang berbeda-beda tentunya membawa hasil yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, jika kita memotret suatu objek dengan angle, teknik, dan metode yang berlainan, tentu akan didapat hasil yang bermacam-macam pula.
Polemik seputar cara membaca atau menafsiri Alquran telah ada semenjak zaman antik Islam. Jalan panjang dan berliku pembacaan dan penafsiran Alquran tersebut telah melahirkan berbagai macam aliran/kelompok Islam mulai dari muktazilah, jabbariyah, asy’ariyah, murji’ah dan lainnya. Penafsiran Alquran secara politis juga melahirkan berbagai macam kelompok, seperti sunni, syi’ah, dan khawarij. Sampai sekarang tercatat berbagai macam identitas Islam mulai yang disebut fundamentalis, liberal, transformatif, tradisionalis, Islam kiri dan lain sebagainya. Semua ini adalah efek dari perspektif terhadap tafsir Alquran yang berbeda-beda. Bahkan di Indonesia sendiri kita lihat banyak sekali organisasi beridentitas Islam mulai dari NU, Muhamadiyah, Al Irsyad, HTI, MMI, FPI, JIL, Ahmadiyah, dan lain-lainnya yang semuanya mempunyai pemikiran dan doktrin yang berbeda-beda.
Alquran yang terus open ended
Keragaman dalam menafsiri Alquran tentu tidak lepas dari aspek kesejarahan Alquran sendiri.
Alquran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun melalui Nabi Muhammad tentu merupakan bentuk intervensi langsung dari Allah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi waktu itu. Allah secara langsung mengirimkan kalam-Nya yang transeden dan eternal melalui Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kemudian diteruskan ke umat manusia sebagai petunjuk hidup dalam bentuk bahasa Arab yang menyejarah dan kontekstual.
Tidak ada problem yang terjadi seputar pengertian dan tafsir ayat-ayat Alquran semasa Nabi masih hidup. Karena, setiap ada masalah, bisa langsung dikonfirmasikan kepada Nabi dan beres.
Namun permasalahan mulai terjadi setelah wafatnya Nabi. Polemik seputar tafsir bahkan qiroat (bacaan) Alquran mulai muncul. Untuk qiroat Alquran, tercatat terdapat beberapa macam. Sampai pada khalifah Utsman bin Affan, Alquran kemudian dikodifikasi menurut “selera” Khalifah Utsman dan ahli-ahlinya menjadi korpus yang tertutup. Hasil kodifikasi itu dikenal sebagai Mushaf Utsmani, mushaf seperti yang kita baca sekarang ini (meski secara tanda-tanda linguistik berkembang dan berubah).
Polemik seputar tafsir Alquran berlangsung lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai terjadi aksi kafir-mengkafirkan dan pertumpahan darah akibat perspektif yang berbeda-beda dalam menafsiri alqur’an, baik dari motif filosofis maupun politis. Bahkan dendam kesumat akibat efek yang terjadi 1400-an tahun yang lalu seputar konflik tafsir “politis” yang berbeda antara sunni dan syiah masih berlangsung sampai sekarang. Lihatlah aksi-aksi bom bunuh diri silih berganti terjadi antara pengikut sunni dan syiah di Iraq yang mengakibatkan banyak korban bergelimpangan. Ya, agama Islam yang harusnya membawa kedamaian malah menjadi tragedi berdarah yang berlangsung terus menerus bagai labirin yang tak berujung. Cukup menyedihkan.
Kembali ke Alquran. Allah menurunkan Alquran hanyalah sekali melalui Nabi Muhammad dan itu telah berlangsung 14 abad yang lampau, dengan segala keterbatasan kondisinya waktu itu (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan geografis). Sesuai dengan firmanNya, Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang terakhir dan diwahyukan melalui Nabi yang terakhir pula, yaitu Muhammad. Tidak mungkin ada sequel Alquran atau Alquran edisi revisi misalnya untuk zaman sekarang maupun masa mendatang. Sebagai teks yang juga telah menyejarah, Alquran tentu sekarang telah menjadi barang antik tapi populer. Antik disini diartikan merupakan teks kebahasaan yang menyejarah karena dicipta 14 abad yang lalu. Dan populer karena masih banyak orang yang secara terus menerus menafsirkan, memperhatikan dan memilikinya.
“Pengarang” dalam hal ini Allah tidak mungkin kita mintai legalisasi terhadap maksud tertentu suatu ayat. Dan Nabi Muhammad sebagai otoritas distributor pun telah tiada, hingga yang tersisa sekarang hanyalah hadits-hadits Nabi dan kumpulan tafsir dan pendapat fuqoha’ yang tentunya juga terikat konteks zaman dan makan. Hal ini berakibat Alquran sekarang ini adalah open ended. Kita sebagai pembaca diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk menakwil dan memahami Alquran secara proporsional dan kreatif untuk membantu memecahkan problem-problem kita sekarang ini. Alquran dalam hal ini diibaratkan hardware, yang tak akan mungkin berguna apabila belum disentuh atau dimasuki dengan metode penafsiran/penakwilan (software) yang brilian dan tepat sasaran. Di samping itu, Alquran juga memerlukan operator/penafsir yang kompeten, berintegritas, dan liberal.
Perlunya sikap pluralisme
Sebagai kitab suci umat Islam, Alquran tentu juga menjadi salah satu identitas primordialnya. Dan permasalahannya, bagaimana kita bersikap atau “membaca” Alquran untuk sekarang ini. Bagaimana kita memperlakukan Alquran dengan benar. Banyak sekali jenis perlakuan masyarakat kita secara pragmatis terhadap Alquran untuk sekarang ini. Mulai yang hanya menjadi objek bacaan ritual yang kering, bahan provokasi dakwah picisan untuk kepentingan tertentu, dan bahkan di sebagian kalangan mistik Alquran menjadi salah satu resep pengobatan atau lebih dikenal mujarobat serta digunakan untuk mengusir jin yang jahat. Di sejumlah kalangan yang moderat, Alquran juga digunakan sebagai spirit utama dalam transformasi di masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan.
Dalam masalah tafsir dalam memahami teks Alquran, telah banyak metode tafsir yang ditawarkan. Mulai metode tafsir klasik yang cenderung literer seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Jalalayn, Tafsirul Manar, Tafsirul Munir hingga metode tafsir kontemporer hermeneutisnya Nasr Hamid Abu Zayd, metode tafsir dekonstruksi-nya Mohammed Arkoun, dan metode tafsir pembebasannya Farid Esack. Kesemuanya, baik yang klasik maupun kontemporer sekarang ini mengklaim metodenya yang paling benar. Layaknya penjual kecap—mereka berteriak: pilih kecapku, kecapku nomor satu. Bahkan ujung-ujungnya tetap stereotip, saling menjelek-jelekkan bahkan mengkafirkan. Nasr Hamid Abu Zayd contohnya, dianggap murtad oleh otoritas ulama Mesir. Nasr Hamid juga dipaksa bercerai dengan istrinya dan bahkan dipaksa mengasingkan diri ke Belanda.
Kelompok fundamentalis menganggap metode tafsir yang diusung Nasr Hamid dan Mohammed Arkoun kebablasan. Nas Hamid dan Arkoun dituduh melecehkan Alquran karena menganggap teks Alquran dapat ditelaah secara hermeneutis, layaknya karya sastra biasa.
Kelompok moderat dan liberal balik menuduh kaum fundamentalis adalah jumud dan terlalu konservatif. Mereka masih saja bergelut dengan “mimpi-mimpi salafiyyah”. Mereka juga cenderung memuja dan menyembah Alquran secara membabi buta, tanpa mampu untuk melepaskan “mimpi” mereka dan berhadapan dengan kenyataan yaitu ketidakadilan dan penindasan kemanusiaan yang berlarut-larut.
Bagaimana posisi kita sebagai muslim dalam menyikapi permasalahan perseteruan tersebut? Semua realitas itu menuntut kita untuk bersikap bijak dan lebih hati-hati dalam menyikapi keadaan. Kita mau tidak mau memang harus punya pilihan dalam menyikapi problem tafsir kitab suci tersebut. Apakah kita cenderung sepakat dengan pendapat kelompok ini atau lebih condong ke pendapat kelompok itu atau malah punya pilihan tafsir sendiri. Namun yang lebih penting, sikap pluralisme perlu kita kedepankan. Sikap yang mau menerima dan menghargai kehadiran “yang lain” yang berbeda dengan kita. Karena kebenaran absolut adalah milik Allah. Apalah artinya bila kita tetap memaksakan kehendak dan keyakinan kita apabila orang lain mempunyai keyakinan kuat lain seperti yang kita punya juga. Bukankah kita sering juga mengucapkan wallahu a’lam bi al-shawaab, setelah kita membaca, menulis dan menafsiri suatu ayat Alquran. Hal tersebut mencerminkan kerendah hatian kita bahwa tafsir kita mungkin salah, karena yang paling mengetahui yang sebenarnya adalah Allah shubhanahu wata’ala sendiri.
Lagi pula Alquran sebagai pedoman kita, bukanlah satu-satunya “sumber mata air” hukum bagi kita. Bukanlah dalam suatu riwayat diceritakan bahwa saat Nabi Muhammad melepas Muaz bin Jabbal pergi ke Yaman, Nabi berkata, “Jika kamu menjumpai persoalan, maka carilah dalam Alquran. Jika tidak ada, carilah dalam sunnahku. Tapi jika dalam dua sumber itu tidak ada, berijtihadlah dengan pikiranmu yang sehat.” Dari riwayat itu maka kita dapat menarik pemahaman bahwa Alquran sebagai korpus tertutup, terlalu sempit untuk kita jadikan satu-satunya sumber hukum kita. Di samping berpedoman pada Alquran dan sunnah Nabi, kita diberi hak dan kebebasan untuk berijtihad dan berikhtiar sendiri untuk memecahkan suatu masalah demi kemaslahatan bersama.
Alquran sebagai salah satu sumber hukum dan identitas primordial kita sebagai umat Islam, baiknya tetap kita hormati sewajarnya. Alquran juga harus kita apresiasi secara lebih kreatif sehingga melalui spirit religio etiknya dapat memunculkan gerakan yang dapat menghalau eksploitasi dan penindasan terhadap kemanusiaan, seperti apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad di Madinah, Farid Esack di Afrika Selatan, dan Moeslim Abdurrahman (melalui teologi Islam transformatifnya) di Indonesia. Sehingga, sebagai teks yang antik, Alquran tetap bisa menebar pesonanya pada umat Islam—sehingga pula, mengikuti jingle iklan salah satu majalah di Indonesia—Alquran tetap “enak dibaca” dan perlu. Wallahu a’lam bi al-shawaab.***

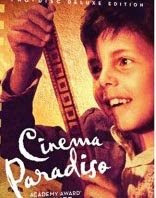
Tidak ada komentar:
Posting Komentar