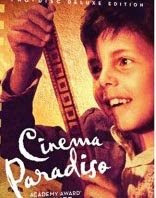Review atas Film Ayat-Ayat Cinta Karya Hanung Bramantyo
Bagaimana seandainya suatu bagian dari film yang sangat Anda sukai tiba-tiba diambil begitu saja untuk digunakan di film lain secara berlebihan. Misalkan saja, bagaimana seandainya score/musik film Godfather yang legendaris itu digunakan untuk film lain, atau misalkan score film Titanic yang masyhur itu dipakai oleh film lain secara jelas sekali dan tanpa “rekayasa” apapun. Terlepas pengambilan atau adopsi musik itu melalui prosedur resmi atau tidak. Mungkin hal ini akan Anda rasakan aneh atau ganjil. Hal semacam inilah yang juga saya rasakan dan agaknya cukup mengganggu saya ketika nonton film Ayat-Ayat Cinta (AAC) arahan Hanung Bramantyo yang saat ini laris di pasaran.
Adalah musik latarnya yang sangat mengejutkan saya. Bukan lagu Ayat-Ayat Cinta yang dibawakan oleh Rossa dan Sherina itu, namun backsound piano dan orkestra yang ada di hampir setiap adegan yang diasumsikan memancing emosi dan keharuan penontonnya. Lihatlah ketika adegan upacara pernikahan Fahri dengan Aisha. Atau ketika Fahri ada di “hotel prodeo” dan kemudian dikunjungi Aisha, atau pas adegan akhir di film ini. Belum lagi adegan-adegan lain—yang tentu saya akan lupa kalau disuruh menyebutkan satu persatu. Backsound adegan-adegan ini, ternyata menjiplak habis-habisan score/music dari film Korea Selatan favorit saya—Taegukgi—arahan sutradara Kang Je Gyu. Film ini diproduksi tahun 2004 dan berhasil menyabet beberapa penghargaan internasional, di samping juga sangat laris di pasaran domestik Korea Selatan sendiri.
Kebetulan saya sangat mengagumi film Kang Je Gyu ini (termasuk score-nya) sampai-sampai saya merekam manual musik latarnya ini menggunakan flash disk untuk sekedar saya dengarkan di komputer saya secara berkala. Memang, kadang kalau saya sangat suka dengan sesuatu, saya tak mudah melupakannya begitu saja. Dan untuk film Taegukgi, karena film ini merupakan one of the greatest film that ever i seen, maka saya rela repot-repot merekamnya, meskipun hasilnya kurang begitu bagus terdengar.
Kembali ke AAC. Film adaptasi dari novel yang berjudul sama karya Habiburrahman El Shirazy ini memang meledak di pasaran dan banyak dibicarakan orang untuk sekarang ini. Mungkin karena “kedorong” dengan kesuksesan novelnya juga, sehingga film ini dinanti-nanti para alumni pembaca novelnya, di samping juga—tahu sendiri lah…omongan dari mulut ke mulut eks penonton dengan calon penonton yang rata-rata para remaja seusia SMP dan SMA, di samping juga dorongan iklan di media yang sangat besar, sehingga sampai minggu ketiga Maret ini, berita yang saya terima menyebutkan bahwa film ini telah ditonton dua juta orang. Jumlah ini tentu besar sekali kalau dibandingkan dengan jumlah penonton untuk film-film
Sebelum nonton, saya cukup sadar dengan “identitas” film ini. Film ini diproduksi MD Entertainment dengan produsernya Duo Punjabi yaitu Dhamoo dan Manoj Punjabi, yang cukup terkenal dengan produksi sinetron popnya di televisi-televisi
Film ini menceritakan kisah Fahri, mahasiswa
Untuk selanjutnya saya sudah tidak bersemangat lagi nonton film ini karena banyak keganjilan-keganjilan lanjutan yang saya lihat. Proses pernikahan Fahri dan Aisha misalnya yang terlihat sangat instan. Bagaimana mungkin urusan nikah kok seperti memilih kucing dalam karung. Fahri cuma ta’aruf dengan Aisha dengan melihat paras ayunya kemudian langsung ho’oh, mau kawin dengannya, tanpa melalui proses “pengenalan dan pengakraban tahap lanjut” misalkan melalui diskusi, tukar pikiran atau sebagainya. Dan inilah yang terjadi ketika Aisha mulai curiga pada sosok Fahri—yang kemudian tersandung kasus kriminal setelah sebulan menikah. Dia “baru mulai” menyelidiki dan menginvestigasi sosok “misterius” suaminya tersebut. “Wah, apa udah nggak kesiangan?,” demikian saya pikir.
Keganjilan lain yang saya dapatkan adalah masalah bahasa. Pada adegan-adegan awal, terlihat bahwa bahasa Arab digunakan pada konteksnya secara benar, misalnya dialog Fahri dengan Maria di awal film. Namun pada beberapa adegan lain, pemakaian bahasa terlihat tidak pas konteksnya. Lihat saja ketika Fahri masuk penjara dan langsung disamperin teman satu selnya dan menyapa dengan memakai bahasa Indonesia. Lho kok? Benar memang, menurut saya, tahanan tersebut adalah orang Mesir atau paling tidak bukan orang Indonesia lah, tapi kok memakai bahasa Indonesia. Juga ketika dialog Aisha dengan pamannya (diperankan Surya Saputra), memakai bahasa Indonesia juga, bukan bahasa Jerman atau Arab misalnya. Dan pas adegan di pengadilan, hakim memakai bahasa Indonesia. Di sinilah menurutku Hanung kurang begitu cermat menggarap hal ini.
Hal lain yang membuatku semakin tidak berharap banyak pada film ini adalah pupusnya menikmati panorama dan keeksotisan Mesir sebagai latar tempat di film ini. Dengan adanya apologi yang menyebutkan, bahwa ada kendala masalah izin syuting di Mesir terkait dengan tingginya biaya, sehingga tidak bisa mengambil gambar di negara ini, dan kemudian agaknya disiasati oleh sutradara dengan lebih banyak mengambil gambar di indoor saja. Untung saja adegan-adegan di dalam ruangan ini banyak tertolong dengan kecemerlangan kamera dalam mengambil angle-angle gambar yang artistik.
Faktor lain yang agaknya cukup mengganggu adalah masalah casting pemain. Banyak pemain di film ini yang menurutku tidak cukup pantas memerankan perannya. Fedi Nuril agaknya kurang begitu tepat memerankan sosok Fahri yang digilai oleh banyak gadis. Karakter dan sosok Fedi terlalu lugu dan lembek di film ini, aktingnya pun biasa saja. Lalu ada banyak pemeran yang menurutku too much Indonesian faces. Lihat saja sosok yang memerankan paman Aisha, si Surya Saputra. Harusnya Hanung berani mencari orang yang betul-betul Jerman, atau minimal bule. Demikian pula sosok Marini yang memerankan Ibu si Maria, yang harusnya sosok permpuan Arab Mesir Koptik tulen. Sosok Rianti Cartwright yang memerankan Aisha juga terlalu MTV sehingga imej tersebut susah dihilangkan.
Akhirnya, hal yang juga patut dicermati dalam film ini adalah pemotretan isu poligami. Fahri—layaknya Don Juan—membuat banyak perempuan di sekitarnya klepek-klepek takluk kepadanya. Meski secara akting dan performa sangat jauh dari harapan, namun secara skenario—tuntutan cerita (dari novel), para perempuan tersebut akhirnya menjadi istri Fahri meskipun terfilter cuma dua orang yaitu Aisha dan Maria. Di sinilah saya kira peran si penulis novel yang menentukan. Habiburrahman menghembuskan isu poligami ini dengan sangat halus, meski pada akhirnya perspektifnya terlihat agak paternalistik, saya kira. Isu poligami yang di Islam sendiri menjadi isu yang terus “panas” dan “kontroversial”, di film ini menemukan suatu bentuk kasusnya tersendiri. Dan yang pasti, saya menduga banyak penonton yang melihat kasus poligami di film AAC ini pasti hanya manggut-manggut saja, mengiyakan, atau saya yakin, pasti sedikit orang yang menolak “deskripsi persuasif” dari penulis novel ini tentang isu poligami.
Secara keseluruhan memang film ini kurang begitu menggigit. Tampaknya ada “energi” yang belum keluar sepenuhnya dari Hanung, sehingga film ini terkesan biasa saja. Dan juga, tak ada sentuhan estetik baru yang ditawarkan Hanung dalam film ini. Mungkin keunikan film ini hanya pada teamnya. Film ini adalah film yang bernafaskan Islami dan dari novel Islami juga, namun disutradarai oleh sutradara “sekuler”, produser “sekuler”, dan para pemain yang mayoritas “sekuler” . Hal lain yang cukup positif adalah, film ini muncul di tengah serbuan film-film bergenre horror yang sedang menyesaki bioskop-bioskop
Taxin