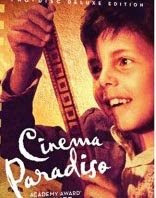“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Q.S. Al-Ahzab: 56)
Semasa sekolah dasar dulu, ada sebuah hari yang sangat spesial yang membuat saya merasa senang setiap kali menjumpainya. Hari tersebut adalah hari Maulid Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal sekolah saya pasti mengadakan suatu seremoni untuk mengenang dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut.
Seperti sudah menjadi kebiasaan pada waktu menyambut hari besar itu, setiap siswa dianjurkan membawa sebungkus kue atau makanan kecil untuk kemudian dikumpulkan di suatu pos yang dijaga seorang guru kami.
Oleh beberapa guru, kumpulan makanan-makanan kecil tersebut kemudian dikompilasikan dengan yang lainnya dalam sebuah bungkus plastik. Setiap bungkus plastik nantinya akan berisi kompilasi 4 atau 5 makanan kecil yang berbeda-beda. Para guru yang bertugas di bagian logistik itu, membuat bungkusan tersebut sejumlah siswa dan guru yang ikut seremoni. Bungkusan-bungkusan plastik berisi kompilasi makanan kecil itu kemudian dibagikan kembali kepada kami para siswa—sebagai “jatah konsumsi” usai acara. Jadi prinsip “demokrasi” yang masyhur itu juga berlaku di acara kami itu khususnya di bagian logistik, yaitu “dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa” .
Dan juga, kalau sebelumnya kita, para siswa membawa sebungkus makanan yang “homogen”, maka setelah usai acara, kita akan mendapat sebungkus makanan kecil juga, namun dalam bentuk yang rupa-rupa alias “heterogen”, dan itulah yang menyenangkan kami, karena laksana pelangi, kompilasi dari berbagai macam makanan kecil itu begitu mempesonakan kami—tentu saja sebagai seorang bocah kecil waktu itu.
Begitulah potret romantisme tradisi Maulid Nabi di sekolah dasar negeri saya waktu itu. Ada rasa gembira dan senang yang saya dapat ketika mengikuti acara tersebut, meski saya tidak terlalu peduli dengan konten acaranya yang sangat klise yang biasanya disusun berurutan, yaitu: pembukaan, sambutan kepala sekolah, pembacaan ayat suci Alquran, materi ceramah umum, kemudian diakhiri doa bersama dan pembagian bungkusan makanan—yang tentu menjadi acara pungkasan terfavorit kami—para siswa.
Sekarang, ketika menjumpai momentum Maulid Nabi lagi, tiba-tiba memori saya sontak kembali ke masa kecil saya tersebut. Ada perasaan geli ketika mengenang masa itu. Masa ketika—substansi (acara Maulid Nabi) saya kesampingkan dan lebih memilih bentuk kemasannya saja (pesona makanan kecilnya).
Kemasan-kemasan acara dalam rangka Maulid Nabi seperti itulah yang sering saya temukan untuk sekarang ini. Bentuknya sering hanya seremoni selebrasif, tanpa menggugah lebih dalam spirit profetik substansi acaranya.
Mencoba Reflektif
Ingin berbeda dengan melakukan sesuatu yang agak berarti setelah mengenang kebengalanku waktu kecil itu, saya memutuskan untuk menelaah dan membaca kembali riwayat hidup Nabi untuk mengisi bulan Maulud ini. Saya ingin sekali “menembus ruang dan waktu”, masuk ke zaman Nabi ribuan tahun lalu, dan mengenal lebih dekat lagi sosok yang tiap hari saya sholawati lewat tasyahud akhir sholat saya itu.
Literatur yang saya pilih guna memuaskan hasrat saya itu adalah bukunya Karen Armstrong berjudul “Muhammad-Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis”, terbitan Risalah Gusti-Surabaya tahun 2001. Alasan saya ingin membaca biografi Nabi lewat tulisan Karen adalah karena saya sebelumnya cukup terpukau dengan bukunya yang lain yaitu “Sejarah Tuhan”. Dalam buku “Sejarah Tuhan”, Karen berhasil mengajak saya “berpetualang” untuk mengetahui peristiwa sejarah ketika Tuhan “ditemukan” dan kemudian disembah oleh berbagai umat beragama dengan berbagai konsepnya tentang Tuhan.
Dalam buku “Muhammad”-nya Karen Armstrong ini (setelah saya baca dengan penuh semangat, karena analisisnya begitu jernih sehingga enak dibaca), saya juga memetik beberapa hal yang cukup berarti. Buku ini berhasil menyajikan potret Muhammad dengan rasa simpati dan hormat—tanpa terlalu bersemangat menyanjung secara berlebihan—dan juga tanpa menghujat layaknya para orientalis zaman dulu.
Dan bagian yang begitu menarik perhatian saya adalah ketika Karen menuliskan bagian-bagian sisi “kemanusiaan” Nabi secara rinci nan memikat.
Lihatlah kutipan berikut yang menggambarkan sosok Nabi yang begitu humanis,
Muhammad memiliki bakat luar biasa dalam spiritual maupun politik—dua-duanya tidak selalu berjalan bersama—dan dia yakin bahwa semua umat beragama punya tanggungjawab masyarakat yang baik dan adil. Dia dapat menjadi sangat marah dan keras, namun dia juga bisa lembut, menghargai, rapuh, dan luar biasa baik. Kita tak pernah mendengar Yesus tertawa, namun sering kita membaca tentang Muhammad tersenyum dan menggoda orang yang dekat dengannya. Kita melihatnya bermain-main dengan anak-anak, menghadapi persoalan dengan istri-istrinya, menangis pilu ketika sahabatnya meninggal dunia, dan memamerkan bayi lelakinya seperti semua ayah yang bangga. (Armstrong, 2001:49).
Kutipan di atas adalah sebagian dari banyak narasi renik yang diungkapkan di buku ini tentang sosok Nabi yang juga “memanusia”. Nabi di sini digambarkan sebagai sosok yang begitu “membumi”, dan tidak hanya sebagai sosok yang selalu dikenal akan status “kelangitannya”. Seperti sebuah perumpamaan yang terkenal, Nabi ibarat batu mutiara di sekumpulan batu hitam biasa, sinarnya indah cemerlang menerangi sekitarnya, namun mutiara itu tetaplah sebuah batu dengan sifat-sifatnya yang lazim untuk ada.
Pada bagian-bagian yang menceritakan humanisme Nabi inilah saya sungguh amat terpesona. Kalau dulu saya membaca sirah Nabi umumnya hanya mengenai hal-hal pokok, agung, dan suci dalam kehidupan Nabi seperti, ketika Nabi pertama menerima wahyu, ketika Nabi hijrah, ketika Nabi Isra’ Mi’raj, ketika melakukan serangkaian peperangan yang heroik, dan akhirnya berhasil menaklukkan Mekkah tanpa pertumpahan darah, namun di buku ini saya berhasil menemukan narasi-narasi kecil lain yang humanis tentang Nabi yang selama ini kurang begitu tergali secara populer dan cuma sayup-sayup terdengar.
Kekuatan lain di buku ini adalah visi ilmiahnya yang kuat yang berjalan beriringan dengan semangat simpatiknya terhadap eksistensi Islam secara umum. Tidak seperti para orientalis zaman dulu yang cuma membahas Muhammad untuk kepentingan politik tertentu. Karen, sebagai seorang yang non-muslimah, tetap bisa fair menjaga ritme gerakan-gerakan narasi sejarah Islam dan Muhammad sonder menistakan secara apriori Islam sendiri, dan juga agama-agama di sekitarnya. Karen menawarkan perbandingan-perbandingan yang informatif antaragama dengan tetap merawat semangat pluralisme yang hakiki.
Saya kemudian berpikir, kalau saja Geert Wilders, pembikin film Fitna yang sangat membenci Islam itu mau membaca dan menelaah buku ini, mungkin dia akan mengurungkan niatnya “menyamakan” Alquran dengan Mein Kampf-nya Hitler, dan menuduh Islam fasis, lewat filmnya itu. Juga andaikata masyarakat Barat mau mengenal Muhammad lewat buku ini, tentu berbagai prasangka buruk akan berganti dengan perasaan simpati.
Dan akhirnya, saya sangat berterima kasih kepada Karen Armstrong yang telah membantu saya mengenang Nabi melalui bukunya ini, sehingga momentum Maulid Nabi ini terasa begitu spesial, karena saya bisa kembali “men-charge” pengetahuan dan kecintaan saya pada Nabi. Meski yang saya lakukan ini tak begitu berarti, namun setidaknya spirit profetik Maulid Nabi dapat meresap ke hati saya. Dan kado kecil saya untuk Nabi, saya ucapkan selalu shalawat dan salam kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya.
Rabiul Awal 1429 H